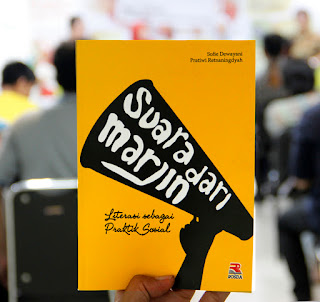Komentar Atas Buku Suara dari Marjin
Oleh: Satria Dharma
Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial
Penulis: Sofie Dewayani & Pratiwi Retnaningdyah
Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Halaman: 229
Tahun terbit: Mei 2017
Harga: Rp78.500
ISBN: 978-602-446-048-8
Penulis: Sofie Dewayani & Pratiwi Retnaningdyah
Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung
Halaman: 229
Tahun terbit: Mei 2017
Harga: Rp78.500
ISBN: 978-602-446-048-8
Apa itu literasi dan mengapa harus ‘dibumikan’? Literasi selama ini memang boleh dikata hanya berupa definisi canggih yang belum benar-benar membumi. Ia hanya dikunyah-kunyah dan dirumus-rumuskan oleh para akademisi di menara gadingnya.
Tentu saja kegiatan literasi telah ada
sebelumnya dan itu bisa dijejaki pada zaman-zaman sebelumnya. Tapi itu masih merupakan
inisiatif-inisiatif perorangan yang sangat elitis, belum merupakan sebuah
gerakan, apalagi berlandaskan semangat keagamaan atau spiritual seperti
dalam Islam.
Bangsa mana saja yang memiliki budaya literasi
tinggi akan menjadi bangsa maju dan berkembang, sebaliknya bangsa yang meninggalkannya akan tertinggal. Literasi menjadi tonggak kebangkitan peradaban, baik di dunia Barat
maupun di dunia Islam. Jadi upaya membangun bangsa sejatinya ialah membangun kembali budaya literasi umat
atau bangsa ini agar kejayaan dapat kita raih kembali.
Rod Welford, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Queensland,
Australia, telah memberi
perhatian khusus untuk literasi. Ia berkata :“Literacy is at the heart of a
student’s ability to learn and succeed in school and beyond. It is essential we
give every student from Prep to Year 12 the best chance to master literacy so
they can meet the challenges of 21st century life.”
Literasi adalah inti atau jantungnya kemampuan
siswa untuk belajar dan berhasil dalam sekolah dan sesudahnya. Tanpa kemampuan
literasi yang memadai, siswa tidak akan dapat menghadapi tantangan-tantangan
Abad Ke-21. Intinya, kemampuan literasi adalah modal
utama bagi generasi muda untuk memenangkan tantangan abad 21. Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Queensland telah mengeluarkan buku Literacy the Key to
Learning: Framework for Action untuk digunakan sebagai acuan
pendidikan mereka pada tahun 2006-2008.
Bagaimana dengan pendidikan literasi di
Indonesia?
Rendahnya reading
literacy bangsa kita saat ini dan di masa depan akan membuat rendahnya daya
saing bangsa dalam persaingan global. “70 persen anak
Indonesia sulit hidup di Abad Ke-21,” demikian kata Prof. Iwan
Pranoto. Peringkat siswa kita di tes PISA terus berada di bawah sejak tahun
2000 sampai sekarang.
Alhamdulillah, sejak turunnya Permendikbud
23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mencantumkan adanya kewajiban bagi
sekolah untuk membudayakan membaca melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), maraklah kegiatan literasi di berbagai daerah,
utamanya di sekolah-sekolah. Gerakan Literasi Sekolah ini bak oasis bagi
hilangnya budaya membaca dan menulis bagi siswa di sekolah selama ini.
Sejak gerakan Gerakan Literasi Sekolah diluncurkan, berbagai daerah seolah berlomba untuk
menunjukkan gairah membaca dan menulis siswa dan guru. Contoh, sejak
dideklarasikan sebagai Provinsi
Literasi setahun lalu, DKI Jakarta berhasil mendorong siswanya untuk membaca
sebanyak satu juta buku. Di Surabaya program Tantangan Membaca Surabaya 2015
berhasil memotivasi 39.000 lebih siswa membaca 20 buku per orang. Siswa di SMAN 5 Surabaya berhasil membaca 1.851 buku hanya dalam dua bulan. Berbagai
sekolah berhasil mendorong siswanya untuk menulis dan menerbitkan karya tulis
dalam bentuk buku. Untuk guru program SAGUSABU (Satu Guru Satu Buku) yang
digawangi oleh Media Guru dan SAGUSABU yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) berhasil
mendorong ribuan guru untuk mulai menulis dan menerbitkan buku mereka sendiri.
Literasi telah dibumikan kembali setelah selama ini menghilang dan tidak pernah
dipahami urgensinya.
Buku Suara
dari Marjin ini unik dan menarik karena ditulis oleh dua orang doktor di
bidang bahasa yang sama-sama menggawangi program Gerakan Literasi Sekolah. Tentu saja mereka berdua sangat
otoritatif untuk berbicara tentang literasi dan bagaimana membumikannya karena sama-sama
berprofesi sebagai dosen yang mengajarkan kemampuan literasi. Yang lebih unik
adalah bahwa buku ini berangkat dari penulisan ulang disertasi mereka ketika
mengambil program doktor. Sofie di
University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, Pratiwi di
University of Melbourne, Australia.
Yang membuatnya sangat menarik adalah bahwa penulisan ulang disertasi ini
dilakukan dengan gaya bahasa populer yang membuatnya seperti sebuah novel saja
laiknya.
Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para
pengambil kebijakan pendidikan, pelaku pendidikan, maupun para aktivis yang bergerak di bidang pendidikan, baik di
sekolah maupun masyarakat. Pemahaman akan konsep literasi yang kontekstual dan autentik dari para pemangku kepentingan di bidang
pendidikan akan mampu memberikan arahan dalam upaya untuk memberdayakan
masyarakat dalam kegiatan literasi. Apa yang telah dilakukan pemerintah melalu
berbagai programnya akan diperkuat dan diperkaya oleh praktik literasi lokal
yang mengakar pada praktik budaya dan jati diri bangsa.
Satria Dharma, Penggagas Gerakan Literasi Sekolah – IGI (Ikatan
Guru Indonesia).
![[HALAMAN GANJIL]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ2BbRfWVqMb2p9wWTh5Ba6PMWzbvMXN8Sz4HVXAt4a-2HlNFIcxoYETrj1kTCOJ9osfgIsddJvdl886yC5eh7ONpBNr9wXXHH-aRojRWzcj-dcXOozzgfRPF_lHlUPJEDAbtW/s828-r/halamanganjil+logotype2010%252C+edit.bmp)